 |
| Juwaini Husen |
ACEH, REAKSIONE.ID Dalam panggung bisnis digital yang keras, muncul satu fenomena yang lebih keras lagi: ambisi mentah yang dibungkus rapi oleh gelar akademis dan pencitraan kelas eksekutif. Aceh tak pernah kekurangan tokoh semacam ini—mereka yang begitu mengidolakan gelar Master, hingga lupa bahwa gelar itu tidak bisa mendandani moral yang compang-camping.
Sosok ini tampil bak pemimpin masa depan dalam brosur pelatihan motivasi—senyum meyakinkan, pakaian rapi, tutur diplomatis. Namun begitu lampu sorot dimatikan, topeng itu terlepas. Yang muncul hanyalah pribadi dengan dendam yang belum selesai, dan kecenderungan alami untuk mengkhianati siapa saja yang menghalangi ambisinya.
Strateginya? Ah, sebuah mahakarya manipulasi kelas menengah—cukup licik untuk merusak, tetapi terlalu dangkal untuk disebut intelijen. Ia mendorong lawan naik ke atas, memuji, memamerkan dukungan, sambil menunggu momen yang tepat untuk mendorongnya jatuh. Seperti meminjamkan tangga untuk kemudian mencabutnya saat seseorang sudah setengah jalan.
Tentu saja, ini semua dibungkus oleh retorika profesional. Sulit membedakan apakah ia sedang berbicara tentang kepentingan organisasi atau sekadar membaca ulang “kata pengantar” skripsinya yang dulu itu.
Untuk memperkuat skenario, ia menyelipkan “tetua” dadakan dalam struktur organisasi. Orang-orang yang tiba-tiba muncul, mengatasnamakan adat, padahal pengetahuannya tentang tradisi lokal mungkin hanya setipis daftar hadir rapat. Diperkenalkan pula “program inovatif” yang jika diteliti lebih jauh, kualitasnya mungkin tidak mencapai level tugas magang mahasiswa.
Tetapi lucunya, skenario itu tumbang oleh hal paling sederhana: suara mayoritas. Publik memilih pemimpin bukan dari intrik, tetapi dari hati nurani. Kandidat pion yang ia dorong-dorong itu justru diterima luas. Dan sang mastermind ambisius mendadak berubah haluan secepat orang yang salah naik bus. Senyum diplomatis tetap dipasang, tentu saja—karena reputasi harus dirawat, meski integritas sudah mubazir.
Lalu muncullah kartu terakhir: kedaerahan. Ia berakting seolah-olah memiliki sertifikat orisinalitas sebagai anak daerah. Padahal kontribusinya bagi daerah lebih tipis dari argumen yang ia gunakan untuk menyudutkan lawannya. Jika kedaerahan adalah soal komitmen dan karya, mungkin ia hanya memenuhi salah satunya—komitmen untuk mempertahankan ego.
Sekarang aroma pengkhianatan yang dulu samar sudah berubah menjadi pekat. Bukan lagi sekadar bau, melainkan asap yang mengepul dari bara ambisi yang terbakar oleh dirinya sendiri. Publik melihatnya. Publik menertawakannya. Dan lebih menyakitkan, publik tidak peduli lagi dengan citra “Master” yang selama ini ia banggakan.
Karma, seperti biasa, bekerja tanpa banyak bicara. Dan berbeda dengan strategi sang eksekutif muda, karma tidak memerlukan pertemuan, tidak butuh dukungan tetua, dan tidak memakai jubah akademis. Ia hanya datang, menagih, dan pergi dengan elegansi dingin yang memalukan siapa pun yang mengandalkan kelicikan sebagai cara naik kelas.
Dan yang paling pahit?
Karma tidak pernah salah target.
Apalagi untuk seseorang yang menyimpannya begitu lama dalam daftar tunggu.
Oleh: Juwaini Husen
Paya Labuy, 16 November 2025.



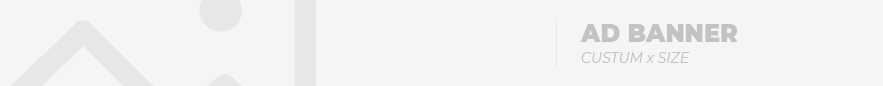
0 Komentar