Oleh: Azhari

Foto: Azhari, S.sy,. MH,. CPM (doc)

ACEH, REAKSIONE.ID | Sebagai daerah yang diberi keistimewaan untuk menerapkan syariat Islam, Aceh bukan hanya dikenal karena qanun-qanunnya yang unik, tetapi juga karena tradisi keilmuan Islamnya yang berakar ratusan tahun. Nama-nama besar seperti Syekh Abdurrauf as-Singkili dan Syamsuddin as-Sumatrani pernah mengharumkan Aceh di pentas dunia Islam. Namun hari ini, di tengah banjir informasi digital dan bebasnya peredaran literatur keagamaan, Aceh menghadapi ancaman baru: infiltrasi paham radikal melalui buku dan kitab yang tidak terverifikasi.
Karena itu, saya melihat penting dan mendesaknya pembentukan bidang khusus di bawah Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh yang secara khusus bertugas memberikan rekomendasi dan pengawasan terhadap peredaran kitab serta buku-buku keislaman di Aceh. Ini bukan bentuk penyensoran pengetahuan, tetapi langkah proteksi terhadap akidah dan harmoni sosial.
Literatur: Penerang Peradaban atau Celah Radikalisasi
Dalam sejarah, banyak gerakan ekstrem tidak lahir dari senjata, melainkan dari buku. Literatur yang dikemas dengan narasi religius—namun secara ideologis bertentangan dengan prinsip moderasi—dapat menyusup ke pesantren, perguruan tinggi, hingga ruang diskusi komunitas muda. Kini, hampir semua buku keagamaan dapat dibeli secara daring tanpa penyaringan isi dan otoritas keilmuan.
Bukan rahasia, ada literatur yang membawa paham takfiri, anti-negara, bahkan menggerus otoritas ulama lokal Aceh. Jika ini dibiarkan, Aceh — yang dikenal moderat dan bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah — dapat menjadi ladang subur penetrasi ideologi yang menyimpang.
MPU Aceh Perlu Peran Baru yang Lebih Strategis
MPU selama ini menjadi rujukan moral dan keagamaan. Namun konteks zaman menuntut peran yang lebih adaptif. Bidang rekomendasi kitab ini tidak perlu tampil sebagai lembaga sensor, tetapi sebagai otoritas validasi ilmiah — yang memberikan panduan terpercaya agar masyarakat tahu mana buku yang sejalan dengan akidah, dan mana yang perlu diwaspadai.
Landasan hukumnya sangat kuat. Qanun No. 9 Tahun 2018 tentang Pembinaan Kehidupan Islami dan UU No. 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh secara eksplisit memberi ruang bagi pengawasan nilai-nilai keagamaan. Ini bukan sekadar pilihan, melainkan tanggung jawab konstitusional.
Belajar dari Malaysia dan Timur Tengah
Malaysia telah lama menerapkan mekanisme ini lewat JAKIM. Beberapa negara Timur Tengah bahkan mewajibkan verifikasi terhadap setiap kitab dan terjemahan Al-Qur’an. Tidak satu pun dari mereka menganggap ini sebagai pembatasan ilmu — justru sebagai penjagaan akidah dan kepercayaan publik.
Dengan status syariat dan warisan intelektualnya, Aceh bahkan seharusnya menjadi model nasional dalam sistem verifikasi literasi keislaman berbasis ulama lokal.
Melindungi Warisan Ilmu, Bukan Menutup Pintu
Aceh pernah memiliki perpustakaan Istana Darud Dunya yang jadi rujukan dunia Melayu. Tradisi keilmuan yang agung itu hanya dapat dipertahankan jika peredaran ilmu di era digital diimbangi dengan pengawasan moral yang kuat.
Pengawasan literatur bukan upaya membatasi pikiran. Ini adalah ikhtiar menjaga agar ilmu yang masuk membawa rahmat, bukan fitnah; penjernihan, bukan provokasi; persatuan, bukan perpecahan.
Penutup
Pembentukan bidang rekomendasi kitab dan buku di bawah MPU Aceh adalah langkah visioner — bukan reaktif. Ini adalah investasi jangka panjang untuk memastikan generasi Aceh tetap tumbuh dalam Islam yang teduh, terbuka, dan beradab.
Jika literasi keagamaan tidak dijaga, yang kita biarkan masuk bukan sekadar buku — tetapi ideologi yang bisa memecah belah peradaban.
Aceh harus tetap berdiri sebagai tanah ulama, tanah ilmu, dan tanah damai.(**)



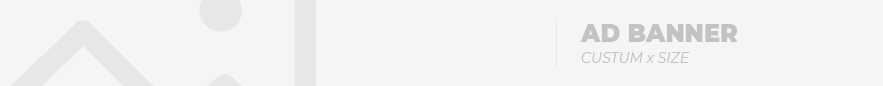
0 Komentar